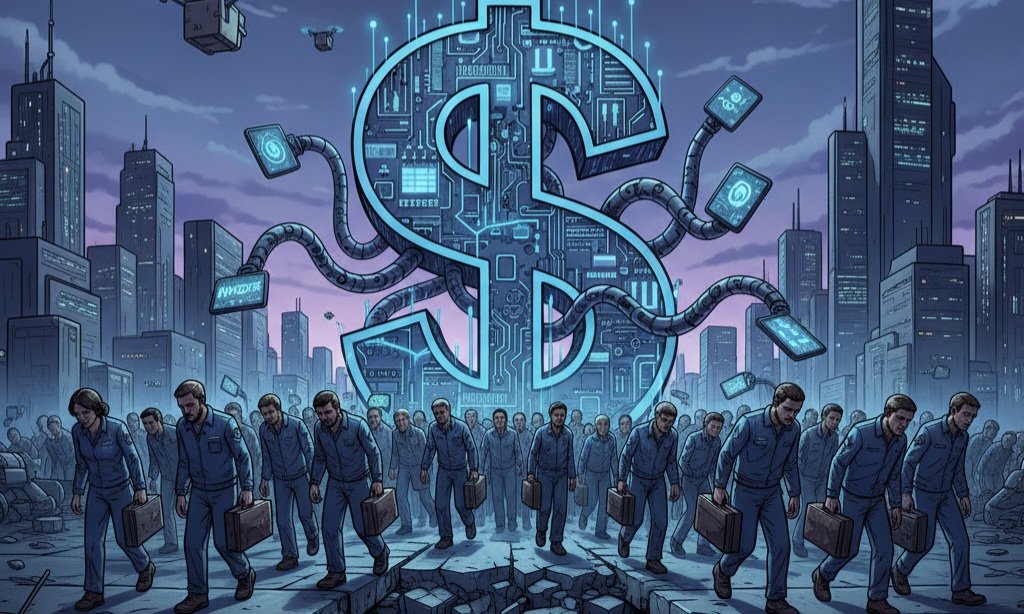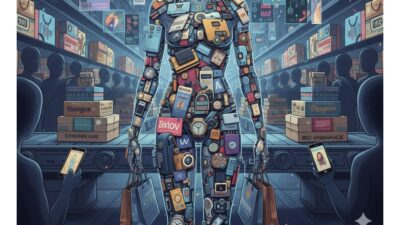EKONOMI – Kehadiran kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dan sistem otomasi kini menimbulkan tekanan struktural baru terhadap tenaga kerja global. Kita tidak lagi berbicara sekadar revolusi industri keempat; kita sudah berada di masa di mana algoritma dan mesin mampu berpikir, belajar, bahkan mengambil keputusan yang dahulu hanya bisa dilakukan manusia. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara produktivitas dan keberlanjutan pekerjaan manusia.
Menurut World Economic Forum (2025), sekitar 40% keterampilan yang ada di pasar kerja saat ini akan menjadi usang dalam lima tahun ke depan akibat penetrasi AI dan otomasi. Ini menandakan bahwa dunia kerja sedang mengalami skill shock — kondisi di mana kecepatan perubahan teknologi melampaui kemampuan adaptasi manusia. Pekerjaan administratif, akuntansi dasar, customer service, hingga desain konten kini dapat digantikan sistem otomatis.
Teori klasik dari Karl Marx tentang “alienasi kerja” menemukan relevansinya kembali. Dalam Manuskrip Ekonomi dan Filsafat (1844), Marx menjelaskan bagaimana pekerja menjadi terasing dari hasil kerjanya karena mesin mengambil alih peran produktif manusia. Kini, alienasi itu tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga kognitif — manusia tersingkir bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena pikirannya kalah cepat dari algoritma.
Namun, berbeda dari masa Revolusi Industri pertama, tantangan kali ini lebih kompleks. Menurut Daniel Susskind dalam A World Without Work (2020), ancaman utama bukan sekadar hilangnya pekerjaan, tetapi redistribusi nilai ekonomi. Teknologi menciptakan nilai besar, tetapi keuntungan lebih banyak mengalir ke pemilik modal, perangkat, dan data, bukan kepada pekerja. Inilah bentuk baru kapitalisme digital — di mana tenaga kerja manusia kehilangan posisi tawar dalam rantai nilai.
Dari sudut pandang teori ekonomi tenaga kerja, Joseph Schumpeter (1942) pernah menyebut fenomena ini sebagai creative destruction — penciptaan inovasi yang sekaligus menghancurkan sistem lama. Dalam konteks AI, kehancuran itu terjadi pada jenis keterampilan yang repetitif dan mudah diajarkan. Tapi bersamaan, muncul peluang baru di bidang analitik, manajemen data, keamanan siber, dan pengembangan algoritma.
Artinya, tantangan utama bukanlah hilangnya pekerjaan, melainkan kecepatan masyarakat dan institusi dalam melakukan reskilling dan upskilling. McKinsey Global Institute (2023) memperkirakan bahwa 375 juta pekerja di dunia perlu beralih profesi atau mempelajari keterampilan baru pada 2030. Sayangnya, sistem pendidikan dan pelatihan konvensional belum cukup adaptif untuk menghadapi realitas ini.
Teori modal manusia (human capital theory) yang dikemukakan oleh Gary Becker (1964) menjelaskan bahwa keterampilan dan pengetahuan adalah bentuk investasi yang menentukan produktivitas dan pendapatan seseorang. Maka, ketika teknologi mengubah permintaan pasar kerja, pekerja yang gagal memperbarui modal manusianya akan terjebak dalam technological unemployment. Dalam konteks Indonesia, ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik.
Kenyataannya, banyak perusahaan kini lebih memilih efisiensi berbasis teknologi daripada ekspansi tenaga kerja. Data dari The Guardian (2025) menunjukkan bahwa lebih dari 60% perusahaan besar di Eropa dan Asia menunda perekrutan tenaga kerja baru karena integrasi AI dianggap lebih ekonomis. Generasi muda (Gen Z) menjadi korban pertama karena sebagian besar pekerjaan entry-level mereka justru paling mudah diotomatisasi.
Namun, tidak semua suram. Jika diarahkan dengan bijak, AI bisa menjadi partner of productivity, bukan pengganti manusia. Erik Brynjolfsson dari Stanford University mengemukakan teori augmentation economy — bahwa AI paling efektif ketika digunakan untuk memperluas kapasitas manusia, bukan menggantikannya.
Dengan demikian, masa depan kerja yang ideal adalah kolaboratif: manusia fokus pada kreativitas, empati, dan penilaian etis, sementara mesin menangani analitik dan rutinitas.
Kebijakan publik dan pendidikan harus merespons perubahan ini secara sistematis. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri perlu membentuk ekosistem pembelajaran berkelanjutan (lifelong learning ecosystem).
Pendidikan tidak lagi cukup berhenti di bangku kuliah; pembaruan keterampilan harus menjadi proses seumur hidup. Di sinilah konsep learning agility — kemampuan belajar dan beradaptasi cepat — menjadi aset utama pekerja modern.
Dalam konteks bisnis Indonesia, transformasi ini menciptakan dilema tersendiri. Banyak UMKM belum siap mengintegrasikan teknologi, sementara tenaga kerja industri tradisional belum memahami kompetensi digital dasar.
Jika tidak segera diantisipasi, AI justru akan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah dan memperkuat urbanisasi digital. Oleh karena itu, program digitalisasi tenaga kerja harus dipadukan dengan pendekatan sosial-ekonomi yang inklusif.
Selain itu, isu etika dan keamanan kerja juga muncul. AI yang mampu melakukan analisis perilaku, memantau kinerja, bahkan menilai produktivitas individu bisa mengancam privasi dan kebebasan pekerja.
Michel Foucault pernah menggambarkan kondisi ini dengan konsep panopticon modern — pengawasan tanpa henti yang membentuk kepatuhan sistemik. Dalam konteks korporasi modern, otomatisasi dapat menciptakan bentuk baru kontrol yang halus tetapi mendalam.
Di sisi lain, sektor pendidikan tinggi dan pelatihan profesional perlu bertransformasi menjadi pusat inovasi keterampilan baru. Model microcredential, bootcamp, dan modular learning harus menggantikan pendekatan konvensional yang kaku.
Kampus bukan lagi tempat menunggu gelar, melainkan laboratorium adaptasi sosial terhadap teknologi. Inilah bentuk konkret reskilling revolution yang diusulkan oleh WEF (2024).
Perusahaan yang cerdas menyadari bahwa investasi pada manusia sama pentingnya dengan investasi pada teknologi. Sebab, mesin yang canggih tanpa manusia yang berdaya akan kehilangan arah moral dan sosial. Organisasi perlu mengadopsi paradigma baru: human-centric automation. Artinya, setiap penerapan teknologi harus memprioritaskan peningkatan martabat dan kapasitas manusia, bukan sekadar efisiensi biaya.
Pada akhirnya, AI bukan ancaman, melainkan ujian bagi kebijaksanaan manusia dalam mengatur relasi antara teknologi dan tenaga kerja. Mereka yang mampu belajar, beradaptasi, dan berinovasi akan bertahan; sementara yang menolak perubahan akan tersingkir.
Dunia bisnis kini menuntut keseimbangan baru: antara efisiensi dan kemanusiaan, antara algoritma dan empati. Di situlah letak peradaban kerja masa depan — bukan di mesin yang cerdas, melainkan pada manusia yang mampu menggunakan kecerdasan dengan bijak. (*)